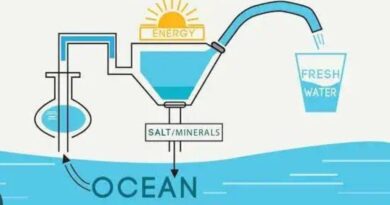Melacak Muasal Mikroplastik
Jakarta, NA (5/10). Dari mana, sih, mikroplastik berasal? Tampaknya, kondisi ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah perkembangan zaman. Kita tahu, seiring waktu, penggunaan plastik semakin disukai, terutama oleh kalangan industri. Ada banyak alasan yang melatarinya. Selain lebih murah—ketimbang bahan lain seperti logam misalnya, plastik juga mudah dibentuk. Ia kuat tetapi ringan, tidak berkarat, dan bersifat termoplastis.
Maka, alat-alat berbahan dasar plastik pun kian mendominasi. Ia bisa ditemukan di hampir setiap sendi kehidupan. Mulai dari kemasan produk makanan dan minuman, tekstil sintetis, hingga produk-produk perawatan dan kosmetik. Demikian juga pada industri besar seperti cat, ban mobil, dan sebagainya, plastik juga sangat mendominasi.
Dengan semakin maraknya penggunaan alat-alat berbahan dasar plastik dalam kehidupan manusia, pada akhirnya alat-alat tersebut terdegradasi menjadi sampah. Inilah yang menjadi kontributor utama kontaminasi mikroplastik pada lingkungan dan rantai makanan. Pasalnya, mikroplastik terbentuk dari sampah-sampah plastik yang kemudian terurai menjadi partikel-partikel kecil hingga menjadi mikroplastik dan selanjutnya menjadi nanoplastik. Partikel-partikel yang hampir tak kasat mata ini kemudian terserap oleh tanah atau terbawa oleh angin dan diserap oleh tubuh melalui air yang dikonsumsi atau udara yang dihirup.
Namun, sedikit berbeda dengan temuan dalam penelitian mikroplastik pada AMDK oleh State University of New York at Fredonia dan Xue-jun Zhou dari Zhe Jiang Institute of Product Quality and Safety Inspection, yang menunjukkan bahwa kontaminasi mikroplastik pada AMDK justru sudah terjadi pada saat pembotolan. Ini tentu lebih mengkhawatirkan lagi. Betapa air mineral yang sekilas nampak bersih sebenarnya sudah membawa kontaminan berupa mikroplastik.
Status mikroplastik
Kendati sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa risiko yang dibawa mikroplastik dan/atau nanoplastik terhadap kesehatan cukup tinggi, tapi “status”-nya masih pada taraf kontaminasi. Ia belum bisa dikatakan sebagai pencemaran. Hal tersebut disampaikan Prof. Etty, yang menegaskan bahwa kontaminasi mikroplastik belum bisa disebut sebagai pencemaran. Pasalnya, dalam standar baku mutu yang dikeluarkan di seluruh dunia—terutama di banyak negara maju, belum ada yang mencantumkan mikroplastik sebagai pencemaran.
“Pencemaran harus keluar atau tidak memenuhi standar baku mutu, sedangkan semua negara maju yang ada di dunia belum memiliki baku mutu untuk pencemaran mikroplastik di perairan ataupun di media lainnya,” jelasnya.
Sudah tentu di Indonesia pun demikian. Mengingat, standar baku mutu di negeri ini mengadopsi standar baku mutu dari negara-negara maju. Sementara, lanjut Prof. Etty, untuk menetapkan baku mutu sendiri diperlukan pengujian toksikologi yang panjang. Termasuk uji pada biota (sesuai baku mutu tempat hidupnya, misalnya baku mutu perairan laut, baku mutu perairan darat, dan sebagainya) yang sensitif terhadap bahan pencemar yang akan diuji, dan diujikan pada beberapa fase hidupnya.
“Mengingat sampai saat ini belum ada satu negara pun yang memiliki baku mutu untuk mikro dan atau nano plastik, maka kita bisa menyebutnya sebagai kontaminasi saja, bukan pencemaran,” tegasnya.
Kendati demikian, kita mesti benar-benar waspada terhadap bahaya kontaminasi mikroplastik. Caranya, lebih bijak dalam penggunaan alat-alat berbahan plastik, dan bijak dalam mengelola sampah plastik. Kita tidak bisa menunggu sampai mikroplastik ataupun nanoplastik naik status menjadi “pencemaran”. Rois Said/berbagai sumber